Editor : Adzkiya Naila
Penulis : Harry Yulianto (Akademisi STIE YPUP Makassar)
Perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi telah menjadi ancaman global yang memaksa dunia beralih ke model ekonomi berkelanjutan. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menyebutkan, 70% dampak krisis lingkungan dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam.
Di sisi lain, desa justru menyimpan potensi besar sebagai pelopor ekonomi hijau. Dengan 70% wilayah Indonesia berupa pedesaan (BPS, 2023), pengelolaan sumber daya lokal berbasis kearifan dan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi solusi menggerakkan perekonomian.
Namun, eksploitasi berlebihan dan minimnya inovasi seringkali membuat desa terjebak dalam kemiskinan ekologis. Data Badan Pusat Statistik (2023) menyebutkan bahwa 56% penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan, dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 60% desa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola secara berkelanjutan, namun hanya 15% yang telah memanfaatkannya secara optimal (KLHK, 2022).
Data UNDP (2022) menyebutkan, 60% ekosistem global mengalami kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Di tengah situasi tersebut, desa justru memiliki potensi menjadi episentrum ekonomi hijau untuk membangun sistem ekonomi berkelanjutan.
Di sinilah, green cooperative (koperasi hijau) hadir sebagai solusi inovatif. Konsep ini menggabungkan prinsip koperasi (gotong royong dan keadilan) dengan praktik ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan ekowisata.
Green cooperative: Integrasi Ekologi, Ekonomi, dan Sosial
Green cooperative adalah koperasi yang mengintegrasikan tiga pilar keberlanjutan, yakni: ekologis, sosial, dan ekonomi. Berbeda dengan koperasi konvensional, model green cooperative tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat.
Prinsip tersebut sejalan dengan laporan International Cooperative Alliance (ICA, 2020) yang menegaskan bahwa koperasi berperan krusial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Model green cooperative menekankan partisipasi aktif masyarakat, seperti di Desa Tenganan (Bali), koperasi ekowisata dikelola secara kolektif oleh warga. Hasilnya, pendapatan masyarakat meningkat 30%, serta melestarikan hutan adat (Wijaya & Sutrisno, 2021). Model tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi komunitas menjadi kunci keberhasilan ekonomi hijau.
Selain itu, koperasi pertanian organik di Bali juga telah membuktikan bahwa penggunaan pupuk kompos dan rotasi tanaman mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 20% (KemenkopUKM, 2023). Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga menjaga kualitas tanah dan air.
Melalui integrasi ekologi, ekonomi, dan sosial, green cooperative membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar mimpi, tetapi aksi nyata yang menyeimbangkan pelestarian alam, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial di tingkat grassroots.
Pilar Utama Green Cooperative di Pedesaan
Untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di pedesaan, green cooperative bertumpu pada pilar utama yang saling terintegrasi.
Pertama, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Koperasi di Desa Kembangarum (Jawa Tengah), mengembangkan agroforestri kopi yang menggabungkan tanaman pangan dan pepohonan. Praktik ini mengurangi erosi dan meningkatkan pendapatan petani (Arifin, 2022).
Kedua, ekonomi sirkular. Di Lombok, koperasi wanita mendaur ulang limbah kain menjadi produk kerajinan bernilai tinggi, mengurangi sampah tekstil hingga 40% (Nurhayati, 2023).
Ketiga, ekowisata berbasis komunitas. Koperasi Wae Rebo (NTT) mengelola homestay ramah lingkungan dan wisata konservasi, sehingga mampu menarik 5.000 wisatawan per tahun (Damanik, 2022).
Keempat, energi terbarukan. Koperasi biogas (Sumba) menggunakan kotoran ternak untuk memasok listrik ke 200 rumah tangga, menghemat biaya energi hingga Rp 1,2 miliar per tahun (UNDP, 2021). Green cooperative di pedesaan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 15% melalui skema usaha kolektif berbasis sumber daya terbarukan (UNDP, 2022).
Dengan keempat pilar tersebut, green cooperative tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menciptakan mata rantai ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa, serta membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.
Potensi Desa sebagai Episentrum Ekonomi Hijau
Desa memiliki modal alam dan budaya yang tidak ternilai. Lahan pertanian subur, hutan adat, serta kearifan lokal dalam mengelola sumber daya menjadi aset utama.
Namun, selama ini, model pembangunan seringkali mengorbankan lingkungan untuk keuntungan jangka pendek, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi pertambangan atau perkebunan monokultur, yang justru merusak ekosistem (UNDP, 2022).
Green cooperative menawarkan paradigma baru, bukan hanya wadah bisnis, tapi gerakan kolektif untuk memperkuat ketahanan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan.
Di sektor pertanian, green cooperative dapat mengadopsi sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman pangan dengan pepohonan, mengurangi erosi, dan meningkatkan produktivitas lahan. Seperti, Koperasi Tani Organik Maju Bersama (Jawa Barat), yang berhasil menaikkan pendapatan petani 40% melalui sertifikasi organik dan pemasaran digital (Wahyudi et al., 2021).
Di bidang energi, green cooperative dapat mengembangkan biogas dari limbah ternak atau panel surya untuk desa terpencil. Program “Desa Mandiri Energi” Kementerian ESDM (2023) menyatakan bahwa 120 desa telah mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional karena inisiatif koperasi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa desa bukan “korban” kerusakan lingkungan, tetapi pemain kunci yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi hijau, melalui model green cooperative yang berpihak kepada alam dan manusia.
Tantangan Implementasi dan Solusi
Meskipun menjanjikan, namun implementasi green cooperative di desa masih menghadapi tantangan. Pertama, kurangnya literasi lingkungan di kalangan masyarakat. Kedua, keterbatasan akses teknologi dan pendanaan. Ketiga, produk hijau seringkali bersaing dengan produk konvensional yang harganya lebih murah.
Solusinya pada kolaborasi multipihak. Pertama, skema pendanaan hibrida, seperti kombinasi Dana Desa, CSR perusahaan, dan crowdfunding, dapat menjadi solusi inovasi untuk program koperasi hijau (UNDP, 2020). Lembaga keuangan perlu menyediakan pembiayaan mikro berbasis lingkungan, seperti yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dengan skema Kredit Hijau Desa (OJK, 2023).
Kedua, pelatihan digital untuk pemasaran produk hijau wajib diintensifkan, seperti Koperasi Wanita Tenun Flores, berhasil mengekspor kain tradisional ke Eropa setelah mendapat pelatihan e-commerce dari KemenkopUKM (2021).
Ketiga, koperasi harus pro aktif membangun jejaring pemasaran dan inovasi digital, misalnya melalui marketplace khusus produk berkelanjutan. Seperti, di Jepara, koperasi pengrajin kayu ramah lingkungan yang menggunakan platform e-commerce untuk menjangkau pasar global, sehingga bisa meningkatkan omzet hingga Rp 500 juta per bulan (Fauzi, 2023).
Kolaborasi Berdampak
Green cooperative tidak bisa bekerja sendiri. Sinergitas multipihak diperlukan untuk membangun ekosistem pendukung. Pemerintah dapat memfasilitasi melalui regulasi, seperti insentif pajak untuk koperasi yang mengadopsi energi terbarukan dan pelatihan manajemen berbasis digital.
Lembaga keuangan perlu merancang skema pembiayaan inovatif, misalnya pinjaman lunak dengan jaminan kelompok. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program CSR, seperti penyediaan teknologi pengolahan limbah.
Akademisi menyediakan inovasi dan pengetahuan berbasis kearifan lokal. Di tingkat desa, masyarakat sebagai pelaku utama yang dapat menjadi kunci perubahan perilaku melalui sekolah maupun kelompok perempuan.
Dengan sinergitas tersebut, mimpi ekonomi berkelanjutan di pedesaan bukanlah utopia. Seperti, kolaborasi antara Koperasi Ekowisata Wae Rebo (NTT) dengan PT. Pertamina yang berhasil mengembangkan homestay ramah lingkungan, sehingga dapat menarik 5.000 turis per tahun (Suryani, 2022). Di tingkat global, dukungan lembaga seperti UNDP dan FAO sangat krusial untuk transfer pengetahuan dan pendanaan.
Gerakan Kembali ke Khittah Koperasi
Green cooperative dapat menjadi bukti bahwa ekonomi berkelanjutan bukanlah utopis. Dengan gotong royong, desa bisa menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan serta penggerak kesejahteraan masyarakat.
Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, pernah berpesan: “Koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan kemakmuran yang adil dan lestari.”
Pesan tersebut relevan dengan spirit green cooperative, yang bukan hanya bisnis semata, melainkan gerakan kolektif untuk kembali ke khittah menyelamatkan lingkungan bumi dan memakmurkan masyarakat pedesaan.
Namun, keberhasilannya bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan progresif, serta kemauan untuk berinovasi. Seperti pepatah, “Banyak sedikit, kita bisa; sendiri tidak akan cukup.”
Pemerintah, masyarakat, dan swasta perlu bersinergi untuk memperkuat green cooperative sebagai tulang punggung ekonomi desa. Dengan sinergitas tersebut, mimpi ekonomi berkelanjutan di pedesaan bukanlah utopia. Jika tidak, maka kita hanya akan mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang.
Mari, jadikan green cooperative sebagai tulang punggung perekonomian desa yang berkelanjutan dan berlestari. Saatnya bertindak dan berdampak, sebelum alam kehilangan kesabarannya.







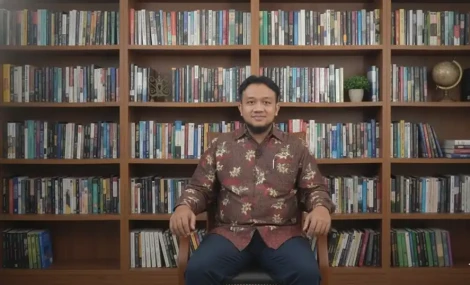

Komentar