Editor : Adzkiya Naila
Penulis : Harry Yulianto, Akademisi STIE YPUP Makassar
Telisiklah sebuah “pasar” yang ramai dan semarak, namun tidak menjual sayur atau barang elektronik. Di lapak-lapak imajiner, para “pedagang” yang notabene diri sendiri, sibuk memajang “barang dagangan” terbaiknya, yakni: kenangan masa sekolah yang dibersihkan dari noda, kesuksesan karier yang dibungkus rapi, maupun penampilan fisik terpoles yang siap “ditawar”. Setiap orang datang dengan katalog kenangan terpilih, siap untuk bertransaksi di “pasar” nostalgia yang hanya digelar sesekali. Suasana hangat dan tawa riang menutupi fakta bahwa ini adalah ajang pamer dan “transaksi jual beli” terselubung.
Apa yang tampak sebagai reuni sekolah atau hanya obrolan ramah di grup alumni, sesungguhnya telah berubah menjadi arena “transaksi” emosional yang kompleks. Di balik sapaan “lama tidak jumpa” dan senyum manis, terjadi pertukaran tidak kasat mata, yakni: pujian ditukar dengan validasi, cerita sukses ditukar dengan kekaguman, dan perhatian kepada mantan yang ditukar dengan kepuasan ego. Interaksi yang terlihat polos, namun menyembunyikan mekanisme pasar yang modern, di mana setiap percakapan dapat bernilai “transaksi” emosional.
Di “pasar” nostalgia, kenangan indah dan mantan telah menjadi komoditas yang “diperjualbelikan” layaknya barang dagangan. Sedangkan, validasi dari orang lain, perhatian yang intens, dan kepuasan ego berperan sebagai “mata uang” yang berlaku di setiap transaksi. Chat pribadi yang penuh dengan “tawar-menawar” perhatian, atau saling puji di kolom komentar yang berisi “penawaran” harga diri, menjadi bukti nyata mekanisme “pasar” nostalgia bekerja. Pada akhirnya, semua pihak (sadar atau tidak) telah menjadi bagian dari siklus “jual-beli” perasaan dan emosional yang paling berbahaya.
Social Exchange Theory dari George Homans (1958) menjelaskan bahwa manusia cenderung melakukan analisis untung-rugi di setiap interaksi sosial. Pada konteks “pasar” nostalgia, setiap “transaksi” emosional mengikuti prinsip: kita menghitung “modal” perhatian yang diberikan dan “keuntungan” validasi yang diharapkan.
“Barang Dagangan” di “Pasar” Nostalgia
Di lapak “pasar” nostalgia, setiap orang hanya memajang “kenangan terpilih” layaknya barang antik yang sudah dipoles ulang. Foto-foto lawas yang dibagikan adalah versi kurasi terbaik, hanya tawa tanpa air mata, dan hanya kemenangan tanpa kegagalan. Kisah pahit dan memalukan disimpan rapat di gudang, sedangkan momen indah dijadikan komoditas andalan. Seperti kata filsuf Søren Kierkegaard (1843), “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards“. Namun di “pasar” tersebut, justru terjebak menjual masa lalu untuk dinikmati di masa kini.
Dalam hierarkis “pasar” nostalgia, mantan pasangan menjadi “barang mewah” yang paling banyak peminatnya. Perhatian mereka dianggap sebagai trophy berharga, bukti bahwa daya tarik masa lalu yang masih berlaku. Setiap chat yang dibalas atau like dari mantan dianggap sebagai “transaksi sukses” yang mengonfirmasi nilai personal. Interaksi dengan mantan menjadi “mata uang” sosial yang paling berharga, lebih bernilai apabila dibandingkan pujian dari puluhan teman biasa.
Tidak hanya kenangan, namun diri sendiri pun menjadi “produk” yang harus dipasarkan secara optimal. Kesuksesan karier, tubuh yang terawat, dan kehidupan keluarga yang tampak harmonis akan menjadi “kemasan premium” untuk meningkatkan nilai jual. Seperti teori dramaturgi Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959), kita semua menjadi aktor yang memainkan “front stage“ performance di panggung reuni sekolah. Setiap cerita kenaikan jabatan atau foto liburan mewah akan menjadi strategi pemasaran untuk meningkatkan tawaran harga diri di “pasar” nostalgia.
“Mata Uang” yang Berlaku di “Pasar”
Dalam kondisi “ekonomi emosional” di “pasar” nostalgia, validasi sosial berfungsi sebagai “mata uang” resmi. Setiap pujian “kamu tidak berubah” di kolom komentar atau reaksi “suka” pada foto lama menjadi bentuk “pembayaran” yang dicari-cari. Transaksi ini mengikuti hukum penawaran dan permintaan: semakin banyak validasi yang diterima, maka semakin tinggi nilai diri yang dirasakan. Fenomena ini mengingatkan pada teori psikolog William James (1890) yang menyatakan, “The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated“, di mana “pasar” nostalgia memanfaatkan prinsip dasar manusiawi dengan sempurna.
Jika validasi sebagai “mata uang”, maka kepuasan ego adalah keuntungan yang dikejar setiap “pedagang”. Perasaan “masih diinginkan” terutama oleh mantan, akan menjadi komoditas paling berharga yang diperjualbelikan. Perhatian dari seseorang di masa lalu, berfungsi seperti sertifikat autentikasi yang mengonfirmasi “nilai jual” diri di masa kini. Di “pasar” ini, ego yang lapar menjadi “konsumen” serta menjadi “komoditas” yang tidak akan pernah puas.
Perhatian yang intens berfungsi sebagai “alat tukar” paling likuid di pasar nostalgia. Chat pribadi yang berisi “tawar-menawar” perhatian, di mana satu pesan dibalas dengan pesan yang lebih panjang, satu kenangan dibayar dengan kenangan yang lebih mesra, sehingga menjadi mekanisme bekerjanya “pasar” secara halus. Filsuf Simone Weil (1947) pernah menulis, “Attention is the rarest and purest form of generosity“. Namun di “pasar” ini, perhatian telah terdegradasi menjadi “alat transaksi”. Setiap detik yang diinvestasikan untuk mengobrol dengan mantan menjadi “mata uang” yang dibayarkan untuk membeli kepuasan sesaat.
Platform media sosial berfungsi sebagai “pameran nostalgia” selama 24 jam non-stop. Fitur “Kenangan” atau “On This Day” menjadi salesman yang tidak kenal lelah, mengantarkan “produk” kenangan langsung ke genggaman “konsumen”.
Budaya digital dapat menciptakan “ekonomi perhatian” yang baru, dimana likes dan komentar akan menjadi “mata uang” yang menentukan “nilai jual” seorang mantan atau kenangan. Semakin banyak engagement yang didapat dari kenangan, maka semakin tinggi “harga pasarnya” dalam bursa emosional di “pasar” nostalgia.
“Pedagang” dan “Pembeli” yang Terjebak dalam Siklus
“Pasar” nostalgia menghidupkan kembali hukum ekonomi paling purba, yakni: penawaran dan permintaan. Ketika seseorang membagikan foto lawas yang langka, mereka sesungguhnya sedang menciptakan “kelangkaan artifisial” yang akan meningkatkan nilai kenangan tersebut. Seperti kata ekonom Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776) tentang kecenderungan manusia untuk “truck, barter, and exchange“, di sini yang dipertukarkan adalah emosi dan perhatian. Setiap balasan chat yang lebih hangat atau pujian yang lebih puitis akan menjadi bentuk “penawaran” yang berharap dibalas dengan “harga” yang setara, sebuah rekognisi atau perhatian khusus.
Mantan yang sulit didekati atau kenangan tertentu yang hanya dimiliki beberapa orang, maka akan dianggap sebagai “limited edition” di “pasar” nostalgia. Status mereka sebagai “barang langka” memicu kompetisi semu dan meningkatkan nilai psikologisnya. Filosofer Prancis Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981) menggambarkan fenomena tersebut sebagai “the simulacrum is never that which conceals the truth, it is the truth which conceals that there is none“. Yang diperebutkan sebenarnya bukanlah orang atau kenangan itu sendiri, melainkan ilusi nilai yang diciptakan tentang mereka.
Pada akhirnya, tidak ada pemenang sejati di “pasar” nostalgia. Semua pihak terjebak dalam siklus “transaksi” tanpa akhir yang hanya “menjual” bayangan dan ilusi. Seperti peringatan penulis Yuval Noah Harari dalam Sapiens (2011) tentang kemampuan manusia menciptakan “fictional realities“, yang terbelit pada realitas fiksi bahwa masa lalu lebih berharga daripada masa kini. Setiap “transaksi” yang tampak menguntungkan hanyalah utang emosional yang akan ditagih di kemudian hari, sehingga akan meninggalkan semua pihak sebagai “pedagang” dan “pembeli” yang sama-sama merugi.
Dampak Berbahaya dari “Perdagangan” Nostalgia
Bahaya terbesar “pasar” nostalgia yakni “devaluasi” hubungan nyata yang dijalani saat ini. Pasangan yang setia setiap hari, tiba-tiba kalah “nilai jual” dibanding mantan yang hanya muncul sesekali di chat. Komitmen jangka panjang terasa membosankan, jika dibanding “produk limited edition” kenangan masa lalu. Seperti peringatan psikolog John Gottman dalam The Seven Principles for Making Marriage Work (1999), “Happy marriages are based on a deep friendship“. Namun, persahabatan mendalam sering kalah glamor oleh kilau kenangan yang dipoles waktu masa lalu.
Hasil survey terhadap 1.000 responden oleh Dating Advice Center (2023) menunjukkan bahwa: 68% orang mengakui pernah terlibat dalam “transaksi emosional” dengan mantan di media sosial, 45% merasa hubungan mereka sekarang terganggu oleh interaksi dengan mantan di dunia digital, serta hanya 22% yang menyadari bahwa ini merupakan bentuk “komodifikasi perasaan”. Temuan tersebut mengonfirmasi hasil observasi filsuf sosial, Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding Media (1964), bahwa “We shape our tools and thereafter our tools shape us”, kita yang menciptakan media digital, dan pada akhirnya media digital yang membentuk kembali pola hubungan, perasaan, dan bahkan moralitas.
Di “pasar” nostalgia, perasaan tulus direduksi menjadi “alat transaksi”. Cinta yang seharusnya suci berubah menjadi “komoditas” yang ditawar, sedangkan kerinduan dijadikan “mata uang” untuk membeli validasi. Setiap chat dengan mantan bukan lagi hanya obrolan, melainkan transaksi di mana kita “membayar” dengan perhatian untuk “membeli” kepuasan ego. Filsuf Jerman Karl Marx dalam das Kapital (1867) berkomentar tentang “commodity fetishism“, dan inilah fetishisme terparah, yakni: ketika perasaan manusia dijadikan “komoditas dagangan”.
Yang paling tragis, penipu terbesar di “pasar” ini adalah diri sendiri. Kita berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa yang dicari adalah koneksi autentik, padahal yang dikejar adalah validasi murahan. Kita menganggap diri sebagai pencari kenangan tulus, padahal kita adalah “pedagang” yang pandai bersandiwara. Seperti kata filsuf Jean-Paul Sartre dalam Being and Nothingness (1943) tentang “bad faith“, kita melakukan penipuan terhadap diri sendiri dengan berdalih tidak melihat motif sebenarnya di balik setiap “transaksi perdagangan” nostalgia.
Neurosains Perilaku Nostalgia
Secara neuropsikologis, perilaku nostalgia dapat mengaktifkan sistem reward di korteks prefrontal yang melepaskan dopamin, yakni zat kimia yang sama dan dilepaskan ketika mengalami kesenangan. Inilah yang membuat kenangan masa lalu terasa seperti “obat” yang membuat ketagihan.
Setiap kali membuka album foto lama atau membaca chat lawas, ibaratkan sedang menyuntikkan dosis kenangan manis yang sengaja disaring oleh memori. Korteks prefrontal dengan setia menyimpan kenangan indah serta menguburkan memori yang pahit, sehingga menciptakan “museum kenangan” yang dikurasi secara selektif.
Menurut Sedikides et al. (2015) dalam Emotion, perilaku nostalgia yang berlebihan dapat menciptakan “comparison trap“, suatu jebakan perbandingan di mana kenangan masa lalu selalu terlihat lebih indah apabila dibandingkan masa kini. Fenomena tersebut pada konteks psikologi kognitif disebut “rosy retrospection“, yakni: kecenderungan psikologis manusia untuk mengingat masa lalu secara tidak akurat dengan lebih positif jika dibandingkan kenyataan sebenarnya, seperti mengenang mantan kekasih laksana relasi tersebut sudah sempurna padahal sebenarnya penuh dengan permasalahan klasik.
Untuk jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan dampak psikologis yang lebih mendalam pada kesehatan mental, yakni: dissatisfaction dengan hubungan sekarang, emotional infidelity yang merusak komitmen, serta identity crisis ketika lebih terikat dengan versi diri masa lalu. Pada konteks ini, psikolog dan filsuf Jerman, Erich Fromm, dalam bukunya The Art of Loving (1956), menyebutkan sebagai ‘the pathology of nostalgia’, suatu kecenderungan untuk melarikan diri dari ketidakpastian masa kini dengan memuja masa lalu yang telah diretas dan disterilkan, sehingga justru menghancurkan kapasitas pada relasi yang autentik di saat ini.
Menjadi “Konsumen” yang Bijak
Menyadari mekanisme bahayanya “pasar” ini, langkah pertama menjadi konsumen bijak adalah menyadari sepenuhnya bahwa kita sedang berada di “pasar” nostalgia. Melalui kesadaran, maka kita tidak lagi menjadi “pembeli” yang naif dan mudah terpikat promosi kenangan palsu. Filsuf Stoic Marcus Aurelius dalam Meditations (180 Masehi) mengingatkan, “The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts“, kesadaranlah yang menentukan kualitas interaksi kita di “pasar” tersebut.
Mengubah peran dari “pedagang aktif”, menjadi “penonton yang bijak”, dengan menikmati reuni sekolah sebagai tontonan menarik tanpa perlu terjun ke arena transaksi. Membawa pulang kenangan indah sebagai hadiah tanpa beban tawar-menawar perhatian terselubung atau validasi. Seperti nasihat psikolog Viktor Frankl dalam Man’s Search for Meaning (1946), “Between stimulus and response there is a space… in that space is our power to choose our response“, di situlah kebebasan untuk memilih hanya menjadi “penikmat”, bukan “peserta aktif”.
Mengalihkan seluruh “modal” emosional (perhatian, waktu, dan energi) untuk berinvestasi pada relasi nyata yang sedang dibangun saat ini. Setiap percakapan bermakna dengan pasangan sah lebih berharga dibandingkan semua transaksi di “pasar” nostalgia. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah mengingatkan, “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ : 32), sebuah peringatan yang mencakup juga zina hati dan pikiran yang bermula dari transaksi yang tidak etis di “pasar” kenangan.
Sebelum terjun ke ‘pasar’ nostalgia, refleksikan pada diri sendiri: Apakah saya ingin benar-benar bersilaturahmi, atau hanya ingin menjadi “pedagang” dan “pembeli” di “pasar” kenangan yang hanya menjual ilusi? Setiap detik yang dihabiskan untuk bertransaksi di pasar semu adalah detik yang dicuri dari kehidupan nyata. Keluarlah dari “pasar” nostalgia dengan jiwa yang utuh, sebelum diri sendiri “terjual” di dalamnya.
Namun, kesadaran terhadap mekanisme “pasar” nostalgia seharusnya tidak membuat sinis, melainkan menjadi “konsumen” yang lebih cerdas. Seperti seorang pembeli yang bijak di pasar tradisional, kita perlu belajar membedakan antara “barang asli” dan “palsu”, antara “relasi autentik” dan “transaksi semu”. Refleksinya bukan lagi “berapa ‘harga diri’ saya di pasar ini?” melainkan “apakah saya ingin menjadi bagian dari pasar ini?”





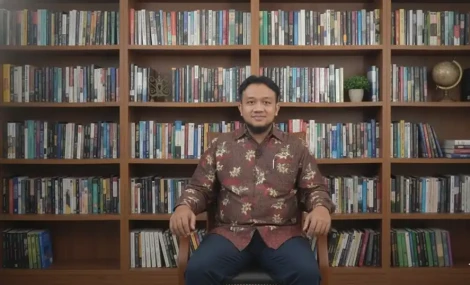



Komentar